Pendahuluan
Pelestarian pusaka (warisan budaya), baik alam maupun budaya hingga saat ini belum dianggap sebagai hal yang penting. Hal itu disebabkan berbagai alasan, mulai dari anggapan bahwa pelestarian adalah anti kemajuan atau perkembangan hingga pada anggapan bahwa pelestarian tidak menguntungkan secara ekonomis. Dengan demikian, dianggap kecil kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Akan tetapi, di beberapa negara maju, pelestarian pusaka alam dan budaya, baik yang tangible (bendawi) maupun intangible (non-bendawi) dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi masyarakatnya serta menjamin keberlanjutan pembangunan.
Berdasarkan pemahaman di atas, warisan budaya Aceh memiliki potensi daya tarik wisata. Warisan budaya mampu menarik pengunjung, baik wisatawan lokal, Nusantara, maupun mancanegara, sehingga warisan budaya dapat menjadi objek dan atraksi wisata utama, bahkan andalan atau icon di Aceh. Negara-negara maju di dunia, seperti Prancis mampu menarik kunjungan wisatawan dalam jumlah besar berkat kekayaan dan keanekaragaman produk warisan budayanya.
Pengembangan warisan budaya sangat erat kaitannya dengan pelestarian kebudayaan. Upaya-upaya pelestarian kebudayaan, meliputi: perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Pemanfaatan, meliputi upaya-upaya untuk menggunakan hasil-hasil budaya untuk berbagai keperluan, seperti untuk menekankan citra identitas suatu bangsa, untuk pendidikan kesadaran budaya, muatan industri budaya, dan daya tarik wisata.
Satu di antara warisan budaya masyarakat Aceh yang bernilai tinggi adalah tenun dan sulaman Aceh. Kain tenun dan sulaman seharusnya dapat menjadi daya tarik dan memberikan informasi yang lebih banyak bagi wisatawan, baik mengenai pengetahuan tentang kain tenun dan sulaman maupun peristiwa yang berhubungan dengannya. Dengan demikian, kain tenun dan sulaman seharusnya diinformasikan kepada masyarakat Aceh khususnya supaya mereka mengetahui terhadap budayanya dan kepada wisatawan pada umumnya. Untuk itu, pada kesempatan ini dijelaskan secara singkat tentang sejarah tenun Aceh, disain, fungsi, dan manfaatnya bagi pengembangan pariwisata budaya di Aceh.
Sejarah Tenun di Aceh
Kebudayaan menenun diperkirakan telah ada sejak tahun 5000 sebelum Masehi di negara Mesopotamia dan Mesir. Kebudayaan ini kemudian berkembang dan menyebar ke Eropa dan Asia sehingga akhirnya sampai ke Indonesia setelah melalui India, China, dan Asia Tenggara. Kapan masuknya kebudayaan menenun ini ke Indonesia belum dapat diketahui secara pasti. Ada dugaan yang menyatakan bahwa kebudayaan menenun mulai berkembang di Indonesia sejak zaman Neolithikum, karena terbukti dengan kayanya tenunan-tenunan Indonesia dengan disain ornamental yang berasal dari stail monumental zaman Neolithikum. Akan tetapi, pendapat lain mengatakan bahwa pada zaman Neolithikum tersebut masyarakat Nusantara masih menggunakan bahan pakaian yang terbuat dari kulit kayu dan kulit binatang, sebagaimana halnya suku bangsa lain yang masih dapat dijumpai hingga sekarang.
Robert Heine Gildern, mempunyai dugaan bahwa kebudayaan menenun dikenal di Indonesia adalah bersamaan dengan menyebarnya kebudayaan Dong-son. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya kesamaan motif pilin (spiral) atau pilin berganda pada motif tenunan Nusantara dengan motif yang terdapat di Dong-son. Hal ini membuktikan tentang adanya pengaruh kebudayaan Dong-son. Pemilik kebudayaan Dong-son sendiri mempraktekkan kepandaian menenun tersebut dengan melihat sisa-sisa pakaian dari zaman perunggu yang berhasil digali di Dong-son.
Kain tenun Aceh
Koleksi Museum Aceh
Berdasarkan hasil penemuan tentang aneka ragam alat-alat tenun yang pernah (dan masih) dipergunakan oleh berbagai suku di Indonesia, dapat diketahui bahwa kebudayaan menenun timbul bersamaan dengan peradaban manusia. Kulit kayu dan kulit binatang yang semula dipergunakan sebagai pakaian (penutup badan), sesuai dengan kemajuan peradaban kemudian diganti dengan pakaian yang diperoleh dengan kepandaian bertenun.
Secara sederhana dapat diterangkan bahwa sebuah kain tenun, dihasilkan oleh perjalinan benang lungsin (benang yang menunggu) dengan benang pakan (benang yang datang). Proses yang sederhana inilah yang kemudian berkembang dengan berbagai teknik yang sesuai dengan kreatifitas manusia, sehingga menghasilkan ciptaan-ciptaan yang indah dan menarik.
Beberapa kelompok masyarakat di Nusantara, menenun merupakan suatu rangkaian upacara tersendiri, yang ditentukan oleh tahapan kerja, dengan tata tertib yang kemudian menjelma menjadi suatu nafas seni budaya. Pada zaman dahulu untuk menenun kain dari jenis-jenis tertentu tidak boleh dilakukan di sebarang waktu. Ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kegiatan menenun dimulai. Hal ini tidaklah mengherankan bila mengingat bahwa beberapa jenis kain di berbagai suku ternyata mempunyai fungsi-fungsi yang khusus.
Khususnya di Aceh, sutera yang ditenun sudah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Ulat sutera banyak dibudidayakan di wilayah Aceh. Catatan paling tua tentang tenunan sutera di Aceh terdapat dalam sebuah kitab Sung (abad ke-10 dan ke-11), yang menyebutkan tentang produksi sutera di Pidie. Pidie merupakan daerah penghasil sutera pada permulaan abad ke-16. Sebagian besar sutera dari Pidie pada waktu itu dikirim ke berbagai wilayah di India. Demikian juga dengan orang-orang Belanda dan Prancis yang berkunjung ke Aceh menyebutkan tentang kain sutera dari Pidie yang sangat berharga dibandingkan dengan kain tenun yang ada di seluruh Sumatera pada waktu itu. John Davis juga menyebutkan tentang banyaknya sutera yang diproduksi di pusat kesultanan Aceh pada abad ke-17.
Sutera Aceh bermutu tinggi sehingga harganya lebih mahal daripada sutera serupa yang diimpor dari India. Menjelang abad ke-19, produksi sutera telah menyebar sampai ke pesisir barat Aceh, meskipun pusatnya tetap berada di Pidie dan Aceh Besar.
Selama abad ke-16 dan ke-17, bahan kain (sutera) merupakan barang dagangan utama dari Aceh yang dikirim ke luar melalui laut. Menurut seorang pengembara bangsa Portugis, Giovanni da Empoli, raja Pasai menjanjikan kepada bangsa Portugis seluruh ekspor sutera negerinya. Hal itu disebabkan bahwa satu di antara hasil produksi penduduk Pasai pada waktu itu adalah sutera, yang berpenduduknya berjumlah 20.000 orang. Selain itu, sutera Aceh juga dijual kepada orang Gujarat sebagai bahan penukar untuk kain dari Cambay serta barang dagangan lainnya hingga seharga 100.000 dukat.
Aceh bukan hanya pengekspor komoditas dagangan ke berbagai daerah, sebagai imbalan untuk berbagai jenis rempah-rempah berharga, tetapi juga mengimpor sejumlah banyak jenis kain dari anak benua India. Kain India merupakan barang dagangan yang sangat umum dan banyak digunakan pada abad ke-15 dan ke-16, sedangkan Aceh merupakan pasar utama bagi kain dari Gujarat. Hingga awal abad ke-19, kain merupakan bahan impor Aceh yang paling berharga. Dalam muatan sebuah junk Cina yang berlayar dari Penang ke Aceh, dari barang senilai 7.600 dolar Spanyol, senilai 2.000 dolarnya terdiri atas kain. Aceh banyak menghasilkan sendiri bahan sutera dan katun, tetapi untuk kain yang digunakan sehari-hari oleh penduduknya berasal dari kain impor.
Satu di antara jenis kain asal India yang beredar di Aceh adalah calico. Pada tahun 1680, VOC (perusahaan dagang Belanda) membuat catatan tentang keuntungan, baik yang diperoleh dengan berdagang chindos maupun patolen, satu di antara jenisnya khusus dibuat untuk orang Aceh. Kain patola dibuat dari benang sutera yang dicelup dan diperdagangkan di seluruh Nusantara pada waktu itu. Khususnya di Aceh, kain patola sangat disukai untuk selendang yang dipakai oleh orang-orang terkemuka di masyarakat.
Alas tempat duduk pengantin yang disulam dengan benang emas
Disain dan Fungsi Tenun Aceh
Di Aceh, selain kerajinan kain tenun juga terkenal dengan kegiatan sulamannya yang menggunakan teknik aplikasi. Warna-warna dan disain banyak dipengaruhi oleh motif-motif yang dibawa oleh para pedagang Arab yang berdatangan pada waktu agama Islam mulai menyebar di daerah Aceh.
Disain yang dipergunakan para penenun di Aceh mencakup serangkaian bentuk garis dan petak dengan pola geometris. Penggunaan benang lungsin dan benang pakan yang berlainan warna akan menghasilkan suatu pengaruh yang menarik pada kain tersebut. Pada waktu itu, teknik yang digunakan adalah teknik ikat, yaitu dibuat sejumlah ikatan kencang pada seberkas benang dengan mengikuti suatu pola hingga pada bagian benang yang tertutup ikatannya tidak terkena warna pada saat dicelupkan. Dengan demikian, Aceh satu-satunya daerah di Nusantara yang benang lungsinnya dibuat secara ikatan. Disain ikat tersebut membentuk mata panah halus yang bersarang dalam lajur berwarna, serupa dengan disain yang terdapat pada disain Batak. Ada kemungkinan orang Batak mengikuti pola disain tenun Aceh.
Disain tekstil yang rumit dan pelik tersebut dikerjakan oleh orang Aceh dengan benang pakan emas dalam tatanan geometris dan bentuk bunga yang menghiasi kain. Disain motif yang paling disukai adalah ular naga yang ditampilkan dalam berbagai ragam. Dalam disain tersebut dimungkinkan terdapat pengaruh Hindu. Akan tetapi, menurut Mens Fier Smedling, sutera Aceh bermotif benang emas merupakan pengaruh dari Persia.
Koleksi disain songket Aceh banyak dihimpun oleh ahli etnologi Belanda, J. Kreemer, pada awal abad ke-20. Selain itu, tekstil sutera Aceh juga tersimpan di Museum Leiden dengan berbagai motif, sebagai berikut: di bagian tengah terdapat pola yang terbentuk dari sejumlah bunga mawar kecil, sedangkan di tepinya berhias motif tumpal dan bunga. Ada juga di antara motif tersebut, yaitu di tengahnya seperti kembang manggis berbentuk bintang, di tepinya bermotif bunga dan tumpal.
Kehebatan tenun Aceh tidak hanya karena rumit dan kepelikannya, tetapi juga pilihan warna yang digunakan begitu kaya dan mencakup berbagai nuansa. Di antara warna yang digunakan adalah hitam, merah, kuning, hijau, biru, dan ungu, merupakan warna yang paling umum digunakan, yang dibuat dari bahan nabati.
Pekerjaan mencelup kain pada abad ke-18 dilukiskan dalam hikayat Pocut Muhammad, sebagai berikut: “lagi dua puluh helai kain telah dipotong, semuanya bahan halus bertepian kuat. Bahan sorban semuanya dicelup berwarna ungu, separuhnya dipotong dan dicelup beraneka warna untuk orang Jawa. Separuhnya lagi untuk bahan bagi tuanku, yang dicelup berwarna merah, merahnya bungong raja (hibiskus). Keusumba (safran) dilindi di sungai dalam jumlah besar sehingga sungai menjadi merah sampai ke muaranya. Air sungai itu tercemar akibat mencelup kain, tuanku.”
Mencelup kain merupakan bagian yang sangat penting dari industri menenun sutera, seperti yang terungkap dalam sebuah daftar panjang bahan celup Aceh yang disusun pada akhir abad ke-19. Di antara bahan celup tersebut adalah Bangko: rebusan kulit pohon ini mengandung bahan pewarna kecoklat-coklatan yang digunakan untuk mencelup kain. Gaca: pacar, tanaman belukar yang daunnya dilumat untuk memerahi (menginai) kuku jari tangan dan kaki. Gaci: kulit pohonnya dilumat dan kemudian direndam dan diperas. Cairannya digunakan untuk mencelup jala ikan. Keusumba: safran, rebusan bunga ini digunakan untuk mencelup sutera, katun, dan benang sehingga menjadi merah tua. Bunga ini banyak dibudidayakan di daerah pedesaan pada waktu itu. Kudrang: rebusan kulit pohon ini digunakan untuk mencelup sutera dan katun agar berwarna kuning. Keumudee: mengkudu, rebusan akar pohon ini digunakan untuk mencelup katun menjadi berwarna merah. Mireh: rebusan kulit pohon ini menghasilkan warna merah untuk bahan celupan kain. Ubar: rebusan kulit pohon ini menghasilkan bahan celupan berwarna merah dan hanya digunakan untuk mencelup jala para nelayan. Ulem: rebusan kulit pohon ini digunakan untuk mencelup sutera dan katun agar berwarna merah. Pohon ini banyak dibudidayakan di desa-desa di Aceh pada zaman dahulu. Reugon: rebusan kulit pohon ini digunakan untuk mencelup kain menjadi berwarna hitam. Seunam: nila atau indigo, bahan pewarna dari daun tanaman belukar yang digunakan untuk mencelup katun menjadi berwarna biru. Seupeueng: sepang atau secang, rebusan kulit pohon ini digunakan sebagai pencelup bahan dari sutera, katun, dan benang agar berwarna merah. Agar tidak memudar, bahan ini dicampurkan dengan gandarukam. Teungge: rebusan kulit pohon ini menghasilkan bahan celupan gelap yang digunakan untuk mencelup kain agar berwarna hitam. Cibree: rebusan kulit pohon ini berguna untuk membangun warna gelap pada kain katun.
Mencelup bahan tenun merupakan pekerjaan yang demikian menentukan dalam proses menenun sehingga orang Aceh beranggapan: “baik sekali jika menginang sirih pada waktu merebus malo, karena merahnya sirih berpengaruh baik atas merahnya bahan celupan. Apabila sempat terjadi bahwa bahan indigo yang disiapkan seorang perempuan tidak menghasilkan warna yang bagus pada bahan sutera, artinya salah seorang kerabatnya akan mendapat musibah kelak”.
Kepandaian menenun tidak saja dipergunakan untuk sekedar menghasilkan hanya kain sebagai penutup tubuh, tapi lebih dari itu kain tersebut dapat merupakan sebuah karya seni yang muncul sesuai dengan alur kehidupan masyarakat. Sehelai kain tenun yang indah, tidak saja berfungsi sebagai busana penutup tubuh, tetapi juga dapat menunjukkan derajat dan martabat si pemakainya.
Sebagaimana halnya sulaman benang emas, sutera digunakan untuk tujuan peragaan dan kemulyaan. Baik laki-laki maupun perempuan mengenakan sehelai sarung sutera di atas celana hitam khas Aceh. Untuk perempuan biasanya mengenakan selendang sutera berukuran panjang dan lebar yang diletakkan di bahu atau sebagai penutup kepala. Para lelaki biasanya menghias topi kebesaran mereka dengan sehelai kain sutera bersegi, hal itu untuk menambah pamor dan wibawanya. Kain tersebut dilipat dalam bentuk sudut bertemu sudut, kemudian dililitkan di sekeliling topi Aceh hingga membentuk kopiah meukeutop.
Kain tenun Aceh
Koleksi Museum Aceh
Bahan celana untuk perempuan juga dibuat dari sutera. Bahan itu dipotong menurut pola yang sempit pada mata kaki dan lebar pada pinggangnya. Celana tersebut diikat dengan pending perak atau emas, kemudian dirancang hingga dapat dipakai untuk semua ukuran.
Pada zaman dahulu di Aceh, sutera juga dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan sirih, yaitu bungkoih ranup. Bungkoih ranub itu digantungkan di atas bahu kiri dan diimbangi oleh sekumpulan anak kunci. Hiasan lain seperti kancing cincin dan tempat tembakau terbuat dari emas, suasa (campuran emas dengan tembaga), dan perak, yang semuanya bergantungan di bagian depan. Perlengkapan tersebut pada umumnya dipakai oleh laki-laki yang sudah berkeluarga. Para pedagang dan saudagar selalu membawa perlengkapan penting itu agar selalu lancar dalam melakukan transaksi bisnis. Apabila seorang laki-laki menjamu, ia menyilakan tamunya mengambil yang ia sukai. Sebaliknya, tamunya akan membalas menawarkan isi setangan sutera sendiri kepada penjamunya.
Memproduksi sutera merupakan suatu proses padat karya dan pada umunya dikerjakan oleh perempuan. Pembudidayaan ulat sutera, mengumpulkan dan memintal suteranya, menghimpun bahan-bahan untuk keperluan mencelup, dan kemudian mencelup benangnya, pada umumnya dikerjakan oleh perempuan. Menyusul kemudian menenun benang sutera, suatu tugas yang membutuhkan ketelitian, mencakup mempersiapkan alat tenun dan mengatur benang lungsin sutera yang halus, menggulung benang pakan pada gelondong, kemudian menenun dan menghitung setiap lembar benang hingga disainya terwujud. Secara umum alat tenun tradisional yang ditemukan di seluruh Asia Tenggara bentuknya hampir sama.
Kain Tenun sebagai Daya Tarik Wisata
Berdasar pada penjelasan di atas dapat dipahami, tenun Aceh menempati kedudukan dan arti penting dalam sejarah dan budaya masyarakat Aceh dan merupakan satu di antara identitas keacehan. Kurangnya informasi tentang kain tenun Aceh dapat menyebabkan wisatawan tidak mengerti dan memahami informasi tentang warisan budaya Aceh tersebut. Ditambah lagi di Aceh saat ini produksi kain tenun dan sulaman sudah sangat langka sehingga keberadaannya semakin tidak dikenal lagi.
Kain tenun dan sulaman seharusnya dapat memberikan informasi yang lebih banyak bagi wisatawan, baik mengenai pengetahuan tentang bendanya maupun peristiwa yang berhubungan dengannya. Dengan demikian, kain tenun dan sulaman yang merupakan satu di antara identitas keacehan menjadi berharga sehingga perlu dipelihara, dirawat, dan diinformasikan kepada masyarakat Aceh khususnya supaya mereka mengetahui terhadap identitasnya dan kepada wisatawan pada umumnya. Untuk itu, kain tenun dan sulaman perlu diinformasikan kepada wisatawan sehingga kain tenun dan sulaman dapat menjadi satu di antara daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Aceh.
Akhir-akhir ini, pariwisata sudah menuju menjadi kegiatan industri besar. Dibandingkan dengan sektor-sektor ekonomi yang lain, periwisata memperlihatkan perkembangan yang relatif stabil daripada yang dialami oleh sektor industri lain.
Fenomena itu menyebabkan banyak negara, wilayah, masyarakat, maupun investor mulai beralih dan melibatkan diri dalam dunia kepariwisataan. Di Indonesia juga sangat menyadari kekuatan sektor tersebut dan terus mengembangkan industri pariwisata di tanah air. Pemerintah daerah mulai menyadari pentingnya pengembangkan sektor pariwisata di daerahnya. Kebijakan-kebijakan di bidang pariwisata yang dibuat dalam rangka mendorong segala potensi daerahnya untuk mengembangkan atraksi, produk, dan destinasi wisata.
Namun demikian, sering terjadi, kegiatan pariwisata membawa dampak negatif, baik pada lingkungan alam maupun sosial budaya dan peninggalan budaya. Akan tetapi, apabila dalam kegiatan pariwisata yang terkonsep dengan baik dan tertata rapi, dampak dari kegiatan pariwisata dapat diminimalisasi. Hal itu disebabkan, pariwisata tidak menjual peninggalan budaya melainkan keindahan, nilai, dan maknanya.
Apabila pariwisata tidak dikelola dengan benar, warisan budaya yang dieksploitasi oleh para operator wisata demi keuntungannya dapat merusak pariwisata itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa pariwisata itu sendiri dapat membantu upaya pelestarian pusaka budaya.
Selama ini apa yang sering dipikirkan orang adalah bagaimana “menjual” aset budaya untuk pariwisata. Demi hal tersebut, misalnya, banyak kesenian yang terpaksa disederhanakan dan dikemas sesuai dengan selera dunia wisata, dan ini banyak dikeluhkan oleh para seniman “asli” karena kesenian tersebut menjadi sekedar komoditas dan tidak lagi memiliki makna. Di beberapa tempat wisata, atraksi diselenggarakan secara asal-asalan, atau banyak promosi yang disebarluaskan namun sebenarnya belum ada kesiapan dari apa yang dipromosikan. Sebagai penjual biasanya ia selalu ingin agar dagangannya laku sebanyak-banyaknya dan mendapat untung sebesar-besarnya, tapi sering lupa menjaga kualitas barang dagangannya agar memuaskan pembeli.
Kipas yang disulam dengan benang emas
Penutup
Selama ini, orang selalu mengaitkan pariwisata dengan pembangunan ekonomi. Pariwisata dianggap sebagai sarana untuk menjaring keuntungan materi. Namun demikian, tidak banyak yang mengaitkan kegiatan pariwisata dengan usaha pembinaan dan pengembangan kebudayaan. Kesan seperti itu tidak salah, karena memang kegiatan pariwisata meyebabkan berkembangnya industri pariwisata yang membuka peluang usaha serta lapangan kerja.
Di samping kelebihan dan nilai ekonomis yang menjanjikan dari pengembangan pariwisata, industri pariwisata juga memberikan dampak negatif bagi kelangsungan tinggalan budaya. Pertumbuhan pariwisata yang tinggi menimbulkan distorsi, kerusakan, dan pencemaran terhadap tinggalan budaya. Mungkin itulah yang disebut banyak kalangan sebagai pengaruh pariwisata terhadap lingkungan sosial-budaya, yang terkadang dijadikan sebagai alasan untuk mengontrol pengembangan pariwisata.
Demikianlah halnya dengan kain tenun (sutera) dan sulaman di Aceh telah kehilangan kedudukannya yang pernah menonjol pada zaman dahulu. Hanya sebagian kecil orang Aceh yang masih melestarikan kerajinan kuno tersebut. Betapapun dengan kehadiran benang emas dan sutera impor, sebagian kecil masyarakat tetap melanjutkan memakai alat tenun tradisional dan menghasilkan disain tradisional demi mengenang kejayaan yang pernah diraih oleh nenek moyangnya pada zaman dahulu. Mereka menghasilkan berbagai jenis kain dengan beraneka ragam motif yang sesuai dengan daerahnya. Jenis kain yang dihasilkan, antara lain jenis-jenis kain sarung, kain songket, kain selendang, kain tangkulok, dan jenis kain panjang. Sebagian dari warisan budaya tersebut dapat disaksikan di museum Aceh dan koleksi Harun Keuchik Leumik di Banda Aceh.
Mengantisipasi pudarnya warisan budaya Aceh tersebut, perlu dilakukan pelestarian. Secara umum pengertian pelestarian adalah upaya mempertahankan keadaan asli warisan budaya, dengan tidak mengubah dan tetap mempertahankan kelangsungannya dengan kondisinya yang sekarang (exitingcondition). Pelestarian juga mempunyai pengertian perlindungan dan pemeliharaan dari kemusnahan atau kerusakan. Pelestarian tersebut dapat dicapai melalui berbagai upaya seperti pengumpulan, pendataan, konservasi, preparasi, rekonstruksi, serta rehabilitasi. Dengan demikian, pelestarian warisan budaya meliputi pelestarian terhadap nilai dan fisiknya.
Penulis: Sudirman, peneliti Balai Pelestarian Sejarah & Nilai Tradisional (BPSNT) Aceh.

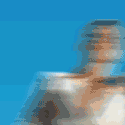

 Gampong Pande, gampong yang luluh lantak digoyang gempa dan dihempas tsunami 26 Desember 2004 lalu itu makam raja-raja terbujur mengabarkan kemegahannya pada masa lalu.
Gampong Pande, gampong yang luluh lantak digoyang gempa dan dihempas tsunami 26 Desember 2004 lalu itu makam raja-raja terbujur mengabarkan kemegahannya pada masa lalu.
 Buah pikiran Snouck tentang Aceh itu terhimpun dalam De Atjèhers, yang dalam edisi Indonesia berjudul Aceh di Mata Kolonial, terbitan Yayasan Soko Guru, Jakarta 1985. Dalam terbitan lain, meski isinya sama, buku ini diberi judul Aceh; Rakyat dan Adat Istiadatnya.
Buah pikiran Snouck tentang Aceh itu terhimpun dalam De Atjèhers, yang dalam edisi Indonesia berjudul Aceh di Mata Kolonial, terbitan Yayasan Soko Guru, Jakarta 1985. Dalam terbitan lain, meski isinya sama, buku ini diberi judul Aceh; Rakyat dan Adat Istiadatnya.






